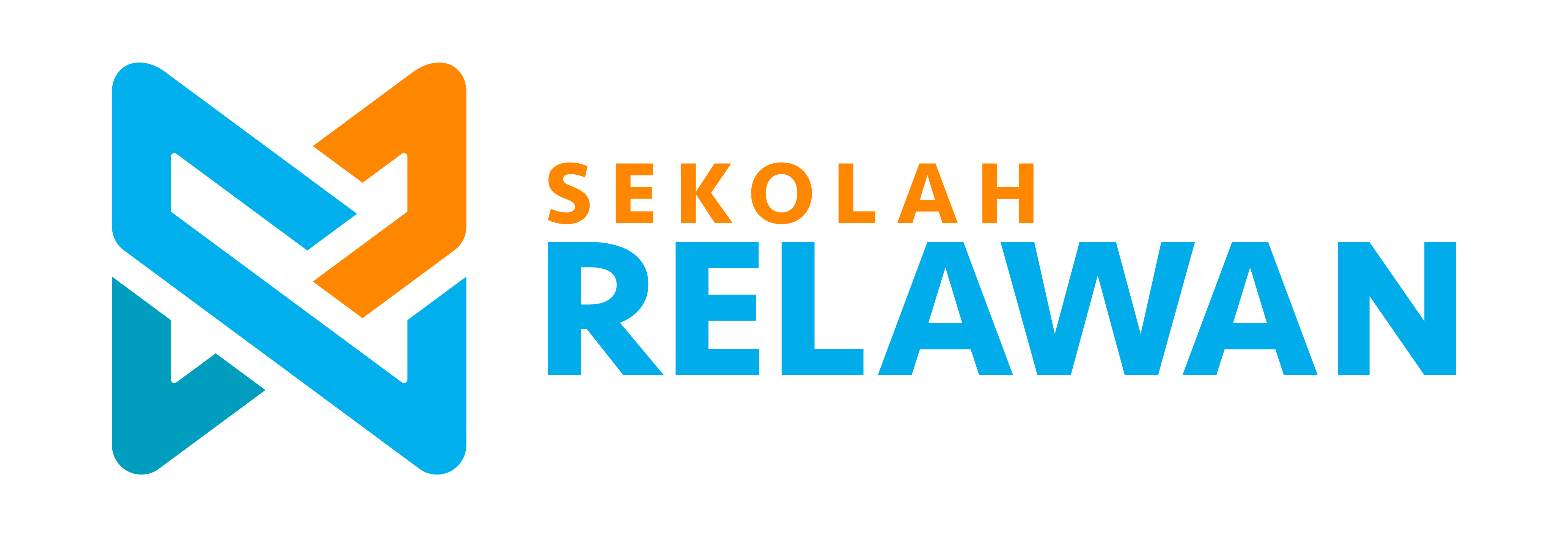Kearifan Lokal Nusantara: Menjaga Lingkungan dari Masa ke Masa
Upaya menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya lahir dari kebijakan negara atau teknologi modern. Jauh sebelum wacana konservasi dan pembangunan berkelanjutan diperkenalkan, masyarakat Nusantara telah memiliki cara mereka sendiri untuk mengelola alam. Melalui kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, komunitas-komunitas adat di berbagai daerah membangun sistem yang tidak hanya menjaga keseimbangan ekologi, tetapi juga memperkuat tatanan sosial.
Subak di Bali: Harmoni Air dan Sosial
Di Bali, masyarakat petani mengembangkan sistem pengelolaan air yang dikenal dengan subak. Subak bukan sekadar infrastruktur irigasi yang memastikan distribusi air berjalan merata, melainkan juga sebuah sistem sosial. Setiap sengketa mengenai air diselesaikan melalui musyawarah para petani dalam forum subak, sehingga keadilan dan kebersamaan menjadi fondasi utama.
Bukti arkeologis menunjukkan bahwa sistem subak telah ada sejak abad ke-11, pada masa pemerintahan Raja Anak Wungsu. Artinya, lebih dari seribu tahun lalu masyarakat Bali telah mempraktikkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Kini, subak tidak hanya berfungsi sebagai sistem irigasi, tetapi juga diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia karena nilai ekologis, sosial, dan spiritualnya.
Orang Samin di Blora: Falsafah Cukup dan Tanggung Jawab
Di Blora, Jawa Tengah, komunitas Samin atau wong sikep juga memiliki pandangan khas terhadap alam. Diajarkan oleh Samin Surosentiko (1859), mereka meyakini bahwa alam adalah anugerah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Prinsipnya sederhana: “mengambil secukupnya” tanpa merusak keseimbangan.
Mereka menolak eksploitasi sumber daya, termasuk air, untuk diperjualbelikan. Sungai, misalnya, hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan untuk dieksploitasi demi keuntungan ekonomi. Falsafah hidup ini menjadi perlawanan sunyi terhadap praktik eksploitatif yang kerap merusak alam. Hingga kini, nilai tersebut tetap hidup di kalangan pengikutnya.
Masyarakat Baduy di Banten: Pengetahuan Ekologi yang Turun-temurun
Di pegunungan Kendeng, masyarakat Baduy telah berabad-abad mempertahankan cara hidup yang berpihak pada alam. Mereka menolak eksploitasi hutan dan tanah oleh pemodal luar, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis dengan pengetahuan tradisional.
Praktik pertanian mereka misalnya, berupa ladang berpindah (huma), sering disalahpahami sebagai pemicu kebakaran hutan. Namun kenyataannya, orang Baduy memiliki pengetahuan mendalam tentang jenis tanah, kandungan humus, hingga kemiringan lereng yang tepat untuk membuka huma. Karena itulah, bencana kebakaran tidak pernah terjadi.
Selain itu, mereka mengenal konsep hutan larangan, yakni kawasan hutan yang dianggap sakral dan tidak boleh diganggu. Ada aturan ketat, ritual, dan waktu tertentu untuk memasukinya. Kepercayaan bahwa roh leluhur masih bersemayam di hutan itu membentuk pagar budaya yang efektif mencegah penebangan liar.
Jejak Hutan Larangan di Nusantara
Konsep hutan larangan bukan hanya milik masyarakat Baduy. Tradisi serupa ditemukan di berbagai wilayah Nusantara, mulai dari Jawa, Sumatra, Bangka, Kalimantan, Buru, Bali, Sumba, hingga Timor. Meski namanya berbeda—ada yang menyebut hutan larangan, hutan suci, atau hutan angker—fungsinya sama: melindungi hutan dari perusakan.
Yang menarik, konsep berbasis spiritualitas ini terbukti efektif menjaga ekosistem. Dengan kata lain, kearifan lokal masyarakat adat tidak hanya soal mitos, tetapi juga strategi konservasi yang lahir dari pengalaman panjang berinteraksi dengan alam.
Menjaga Kearifan, Merawat Alam
Dari Bali hingga Banten, dari Blora hingga pelosok Nusantara lainnya, kita melihat satu benang merah: masyarakat adat mampu menjaga lingkungan melalui kearifan lokal yang menyatukan spiritualitas, sosial, dan ekologi. Mereka tidak mengenal istilah “pembangunan berkelanjutan” sebagaimana dirumuskan dalam forum internasional, tetapi dalam praktiknya mereka telah lebih dahulu menerapkan prinsip itu.
Di tengah ancaman krisis iklim global, kearifan lokal ini bukan sekadar cerita tradisi, melainkan pelajaran penting. Bahwa menjaga alam bukan hanya urusan teknologi, tetapi juga kesadaran kolektif dan tanggung jawab moral untuk hidup selaras dengan bumi.